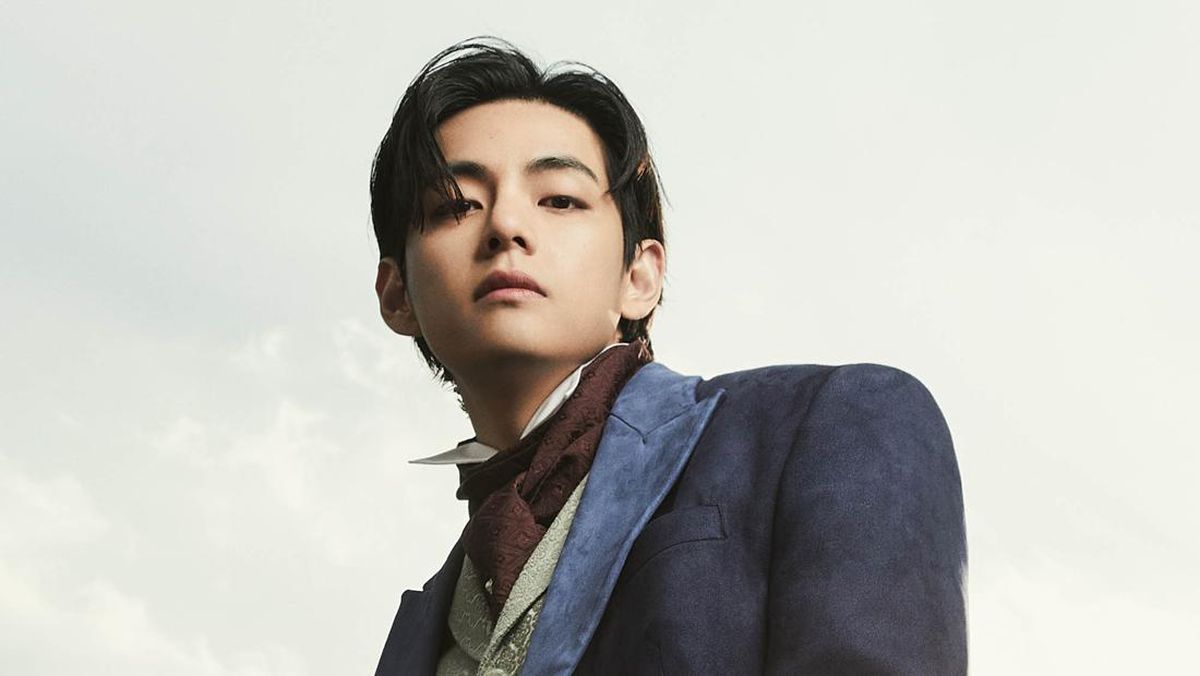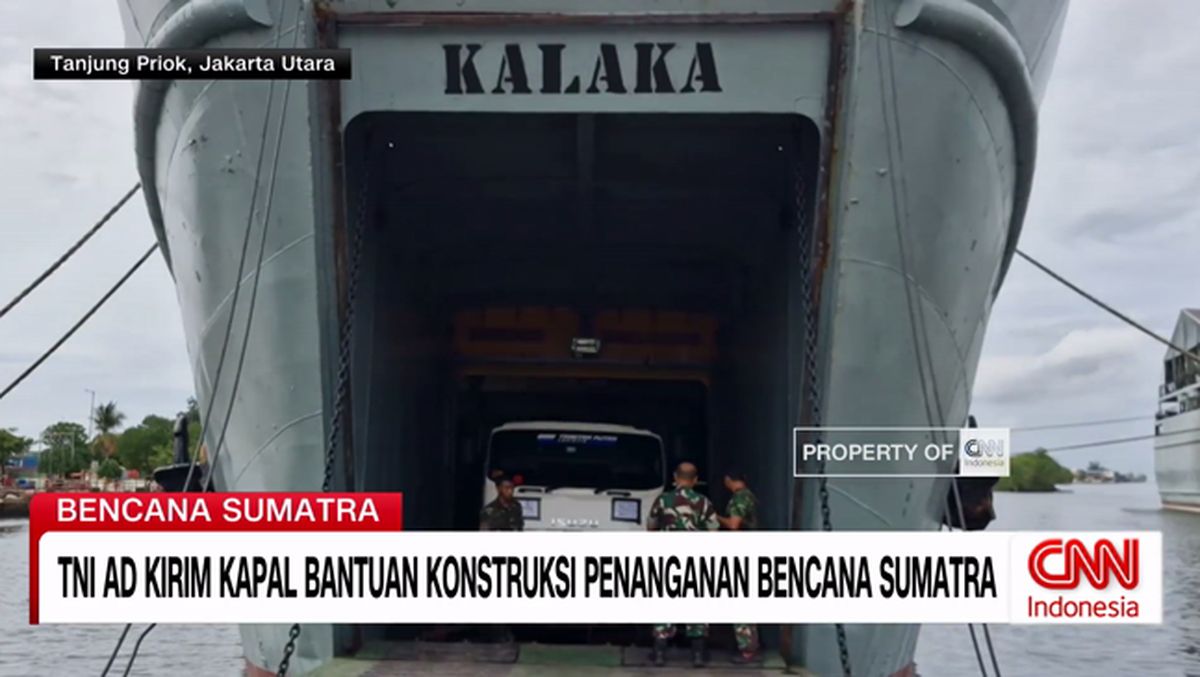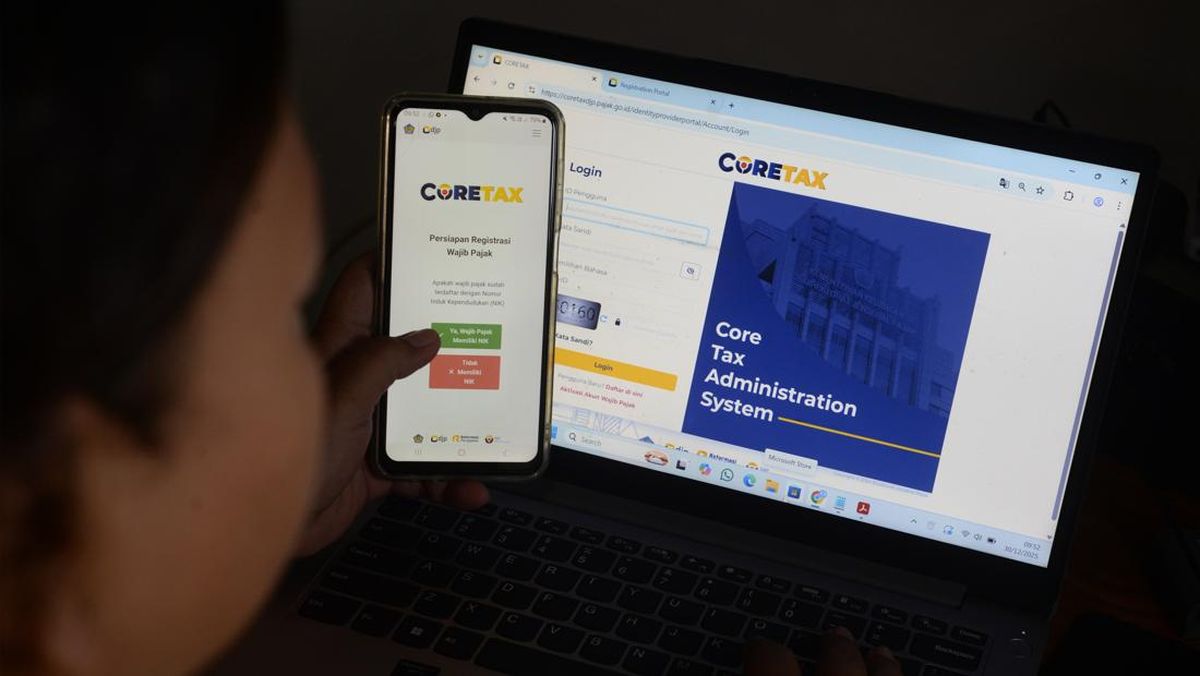Jakarta, CNN Indonesia --
Kemunculan Orde Baru tak bisa dilepaskan dari peristiwa 30 September 1965 dan huru hara politik yang mengikutinya. Lewat peristiwa ini, Soeharto pelan tapi pasti mendapatkan dukungan militer dan politik yang berujung pada pergantian kekuasaan pada 1968.
Peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto berjalan secara perlahan sejak 1 Oktober 1965 hingga 1968. Ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan nasional, tetapi juga mencerminkan transformasi sistem politik dan ideologi yang melahirkan rezim kekuasaan bernama Orde Baru.
Versi resmi pemerintah Orde Baru yang disusun oleh sejarawan militer Nugroho Notosusanto menyebut peristiwa G30S sebagai kudeta yang dirancang oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Namun, dua sejarawan independen, John Roosa dan Victor M. Fic, mencatat bahwa peristiwa ini jauh lebih kompleks, melibatkan dinamika politik dan militer yang akhirnya membuka jalan bagi pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumat, 1 Oktober 1965, sekitar pukul 11.00 siang di Jakarta, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan pengumuman sekaligus pernyataan tentang terbentuknya Dewan Revolusi sebagai kelanjutan dari Gerakan 30 September yang terjadi malam sebelumnya.
G30S, demikian gerakan ini dikenal kemudian, adalah gerakan sejumlah perwira militer di Jakarta yang menculik dan membunuh enam jenderal dan satu perwira muda. Tujuan gerakan ini untuk melibas Dewan Jenderal, sebuah isu yang berkembang kuat saat itu, yaitu sebuah dewan yang disebut-sebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Sukarno.
Namun Dewan Revolusi tak kunjung terbentuk. G30S berhasil dipatahkan sebelum rencana tersebut terwujud. Adalah Soeharto, Panglima Kostrad saat itu, yang memimpin penumpasan G30S tak lama setelah pengumuman RRI disiarkan.
Soeharto sebagai perwira tinggi yang tak masuk daftar penculikan, segera mengambil alih komando Angkatan Darat, mengerahkan pasukan untuk menguasai RRI dan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma yang menjadi basis utama para pelaku G30S.
Tak butuh waktu lama bagi Soeharto menumpas G30S. Victor M. Fic, dalam buku Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi (2005), menyebut Soeharto berhasil menghancurkan kekuatan G30S di Jakarta pada sore hari atau beberapa jam setelah pengumuman Dewan Revolusi.
"Dengan menghancurkan GESTAPU pada pukul 04.00 sore dan meminta Presiden untuk meninggalkan Halim dan menuju ke Bogor pada jam 08.00 malam, di mana ia akan berada di bawah penjagaan Suharto, maka kekuasaan telah pindah ke tangan jenderal itu dan AD, dan tetap berada di sana untuk jangka waktu 32 tahun lamanya."
Sejak saat itulah, meskipun Sukarno secara formal masih menjabat sebagai kepala negara, kendali atas militer dan keamanan nasional telah beralih ke tangan Soeharto.
Kemunculan Supersemar
Operasi penumpasan G30S di Jakarta dilanjutkan dengan operasi dalam skala lebih luas, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Soeharto lewat Angkatan Darat, memburu para kader PKI dan simpatisannya yang dianggap bertanggungjawab atas G30S.
Setelah G30S berhasil dipatahkan, langkah-langkah Soeharto semakin berani. Puncaknya terjadi pada 11 Maret 1966, ketika Sukarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar.
Surat ini memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi memulihkan keamanan dan ketertiban. Berbekal surat tersebut, hanya dalam satu hari Soeharto mengumumkan pembubaran PKI, melarang seluruh organisasi afiliasinya, dan menangkap sejumlah menteri yang dianggap loyal kepada Sukarno.
John Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (2008) menggambarkan momen itu sebagai titik ketika presiden benar-benar kehilangan kontrol atas kekuasaan yang selama dua dekade dipegangnya.
"Ia memilih memenuhi kemauan Soeharto, membiarkan wewenangnya digerogoti, dan akhirnya keluar dari istana tanpa perlawanan," tulis Roosa.
Namun, Supersemar bukanlah dokumen tanpa kontroversi. Victor M. Fic mencatat bahwa naskah asli Supersemar hingga kini tidak pernah ditemukan. Lembaga Arsip Nasional hanya menyimpan dua versi yang berbeda, yakni versi Pusat Penerangan Angkatan Darat dan versi Sekretariat Negara.
"Dua versinya masih terdapat di badan arsip itu... ada perbedaan mencolok antara keduanya".
Meski begitu, Supersemar tetap dijadikan dasar hukum bagi tindakan-tindakan Soeharto yang pada akhirnya mengantarkan Indonesia ke era Orde Baru.
Lewat Supersemar, Soeharto perlahan mulai mendapatkan legitimasi politik dan mulai mengkonsolidasikan kekuasaan. Pada Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mencabut kekuasaan Sukarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, pada Maret 1968, Soeharto dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Awal mula istilah orde baru
Dalam waktu singkat, rezim baru terbentuk dengan tiga pilar utama: stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pemberantasan komunisme.
Untuk meneguhkan legitimasi politiknya, Soeharto menjanjikan penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, pemilu pertama di bawah Orde Baru, baru terlaksana pada 1971, dilanjutkan dengan penyederhanaan sistem kepartaian pada 1973.
Penyederhanaan itu menghasilkan dua partai politik, PDI dan PPP, serta sebuah organisasi politik bernama Golongan Karya.
Golkar yang telah dibentuk jauh sebelumnya, jadi satu-satunya organisasi non partai yang mengikuti pemilu. Golkar juga menjadi kendaraan politik Soeharto selama tiga dekade berkuasa.
Mengutip Historia, istilah "Orde Baru" pertama kali digunakan oleh Jenderal A.H. Nasution pada awal Oktober 1965.
Gagasan tentang tatanan baru yang menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen ini kemudian diadopsi oleh kalangan militer dan intelektual Angkatan 66, serta dipopulerkan dalam sejarah versi resmi pemerintah oleh Nugroho Notosusanto.
Orde Baru digunakan untuk membedakan fase politik sebelumnya di era Soekarno. Rezim Orba menyebut era Soekarno sebagai Orde Lama. Kedua orde ini dipertentangkan dalam banyak aspek, yang pada intinya menegaskan Orde Baru sebagai proses koreksi terhadap kesalahan-kesalahan politik Orde Lama.
Rezim Orde Baru Soeharto berdiri dengan sejumlah fondasi penting, yakni stabilitas politik, prioritas pembangunan ekonomi, kekuasaan yang tersentralistik, peniadaan oposisi, penghancuran komunisme dan dominasi militer.
Keruntuhan orde baru
Soeharto berhasil mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tak pernah dicapai Sukarno. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merebak di berbagai lapisan birokrasi, memperlebar kesenjangan sosial antara elite penguasa dan rakyat.
Orde Baru berakhir pada 1998. Bermula dari krisis moneter Asia yang mengguncang Indonesia. Pada 1997 Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok melonjak, dan jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian. Situasi ini memicu gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi dan pengunduran diri presiden.
Tekanan publik yang kian besar akhirnya membuat Soeharto menyerah. Dengan pengunduran diri tersebut, berakhirlah Orde Baru selama 32 tahun.
Soeharto menjalani sisa hidup bersama keluarganya. Persoalan hukum bermunculan, terutama terkait kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan dirinya dan keluarga.
Pada 31 Maret 2000, kejaksaan Agung menetapkan Soeharto sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi di tujuh yayasan yang dipimpinnya. Meski sudah memasuki persidangan, upaya menghadirkan Soeharto di pengadilan selalu kandas karena berbagai alasan.
Pada 11 Mei 2006 kejaksaan akhirnya menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP3) terhadap Soeharto. Alasan utama penerbitan surat itu karena kondisi kesehatan Soeharto yang semakin menurun.
Namun, Kejaksaan Agung kembali melayangkan gugatan secara perdata kepada Soeharto pada Juli 2007. Yayasan Supersemar termasuk yang digugat. Setelah melalui proses panjang putusan pengadilan hingga PK, Yayasan Supersemar dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. MA menghukum Yayasan Supersemar mengembalikan dana sebesar Rp 4,4 triliun ke negara.
Masa pasca 1998 membawa sejumlah perubahan mendasar: pemilu bebas pertama dilaksanakan pada 1999, dwifungsi ABRI dihapuskan, otonomi daerah diberlakukan, dan kebebasan pers dipulihkan. Namun, sebagaimana dicatat John Roosa, warisan politik Orde Baru tidak sepenuhnya hilang.
Sampai hari ini, masih banyak elite dan masyarakat yang meyakini narasi lama Orde Baru tentang G30S sebagai satu-satunya versi kebenaran peristiwa tersebut. Artinya, meskipun rezim telah berganti, ingatan kolektif bangsa masih dilingkupi oleh konstruksi sejarah yang dibentuk selama tiga dekade kekuasaan Soeharto.
(tas/wis)