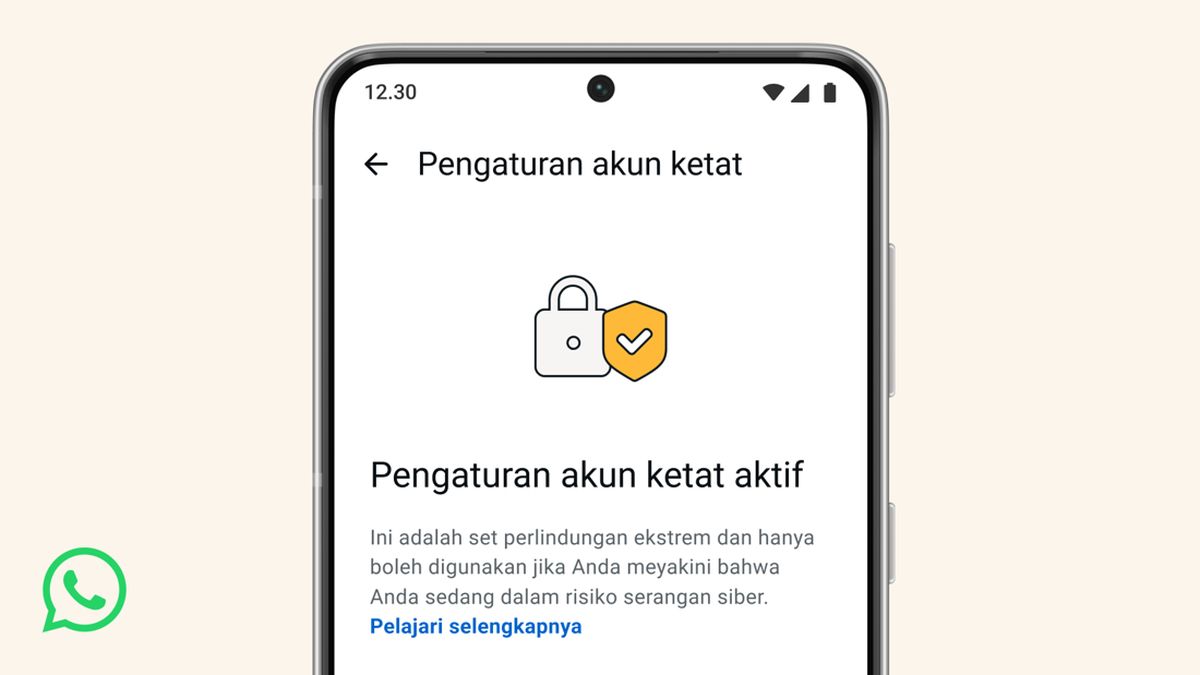Aditya Heru Wardhana | CNN Indonesia
Rabu, 28 Jan 2026 20:15 WIB
 Review The New Yorker: Salah satu kekuatan visual yang ditekankan dalam dokumenter ini adalah konsistensi New Yorker dalam menjaga identitasnya. (Courtesy of Netflix)
Review The New Yorker: Salah satu kekuatan visual yang ditekankan dalam dokumenter ini adalah konsistensi New Yorker dalam menjaga identitasnya. (Courtesy of Netflix)
 Endro Priherdityo
Endro Priherdityo
Bagi yang tertarik mengenai media massa, menyukai seni, dan kesusastraan, New Yorker at 100 tetaplah sebuah tontonan yang layak disimak.
Jakarta, CNN Indonesia --
Dokumenter The New Yorker at 100 mencoba membongkar resep rahasia kombinasi unik antara kata-kata menggigit dan kartun menggelitik yang membuat Majalah New Yorker tetap tegak berdiri hingga menyentuh usia satu abad.
Di tengah gempuran media digital yang serba cepat, majalah ini justru terus berkembang dengan mempertahankan karakter klasiknya.
Melalui alur cerita linier yang kronologis, sutradara Marshall Curry memulai dengan membawa penonton kembali ke masa lalu, tepatnya pada Februari 1925, saat New Yorker pertama kali menyapa pembaca.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Majalah ini dibidani oleh pasangan suami istri, Harold Ross dan Jane Grant. Menariknya, meski Ross merupakan seorang yang putus sekolah, ia memiliki selera artistik dan intelektual yang sangat tinggi.
Hobi Ross bersantap siang di hotel mewah bersama para penulis dan seniman tersohor membentuk visi New Yorker sebagai bacaan eksklusif bagi kaum elit di Manhattan dengan bumbu humor jenis baru yang cerdas. Ross merekrut para penulis cerdas dan seniman hebat yang banyak ia kenal.
Salah satu kekuatan visual yang ditekankan dalam dokumenter ini adalah konsistensi New Yorker dalam menjaga identitas visualnya.
Sejak awal, Ross merancang segala sesuatunya secara estetik, mulai dari desain huruf (font) khusus yang menjadi ciri khas, hingga ikon legendaris Eustace Tilley-sosok pria berbusana trendy dengan topi hitam tinggi yang melihat melalui monokel.
 Editor Seni, Francoise Mouly, memikul tanggung jawab besar untuk menghadirkan sampul yang tidak hanya mencerminkan isi majalah, tetapi juga layak menjadi karya seni abadi yang bisa dibingkai dan dipajang di dinding. (Courtesy of Netflix)
Editor Seni, Francoise Mouly, memikul tanggung jawab besar untuk menghadirkan sampul yang tidak hanya mencerminkan isi majalah, tetapi juga layak menjadi karya seni abadi yang bisa dibingkai dan dipajang di dinding. (Courtesy of Netflix)
Keunikan yang paling mencolok-dan mungkin sulit ditemukan di media lain saat ini-adalah kebijakan sampulnya. New Yorker pantang memajang foto bintang film, model berbikini, atau wajah orang terkenal di sampul mereka. Alih-alih mengikuti tren industri, sampul New Yorker selalu berupa ilustrasi atau lukisan.
Editor Seni, Francoise Mouly, memikul tanggung jawab besar untuk menghadirkan sampul yang tidak hanya mencerminkan isi majalah, tetapi juga layak menjadi karya seni abadi yang bisa dibingkai dan dipajang di dinding.
Gaya visual yang kuat ini bahkan sempat menginspirasi Majalah Pantau di Indonesia untuk menerapkan estetika serupa. Redaksi Pantau juga mengakui dalam cara penyajian informasi dengan bercerita (story telling) macam The New Yorker atau The Atlantic Monthly. Riset dalam, banyak referensi, dan enak dibaca. Meski sayangnya Majalah Pantau tak berumur panjang karena kesulitan keuangan.
Namun, New Yorker bukan sekadar soal sampul yang cantik atau kartun yang lucu. Dokumenter ini mengulas bagaimana majalah tersebut menjadi pionir dalam genre jurnalisme sastrawi.
Salah satu tonggak sejarahnya adalah artikel fenomenal berjudul Hiroshima karya John Hersey pada tahun 1946. Artikel sepanjang 31.000 kata tersebut diterbitkan secara utuh dalam satu edisi.
Hersey turun langsung ke lapangan, mewawancarai enam korban bom atom, dan menulis laporannya dengan teknik bercerita layaknya sebuah fiksi-sebuah pendekatan revolusioner pada zamannya yang mengubah wajah jurnalisme dunia.
 Lensa kamera juga mengikuti penulis Nick Paumgarten yang berkeliling Kota New York. Bermodal notes kecil dan pertanyaan besar, Nick mencari warga yang bersedia diwawancarai mengenai isu politik di Amerika Serikat yang saat itu tengah panas dan memecah belah masyarakat. (Courtesy of Netflix)
Lensa kamera juga mengikuti penulis Nick Paumgarten yang berkeliling Kota New York. Bermodal notes kecil dan pertanyaan besar, Nick mencari warga yang bersedia diwawancarai mengenai isu politik di Amerika Serikat yang saat itu tengah panas dan memecah belah masyarakat. (Courtesy of Netflix)
Di sisi lain, The New Yorker at 100 memberikan ruang bagi penonton untuk melihat proses kerja para awak redaksinya. Editor Kartun, Emma Allen, misalnya, harus menyeleksi lebih dari 1.500 kartun setiap pekannya hanya untuk memilih 10 hingga 15 karya terbaik yang layak cetak.
Hal ini menjadi kontras yang menarik dengan kondisi media massa di Indonesia saat ini, di mana semakin sulit menemukan media yang konsisten menerbitkan kartun satire yang tajam sekaligus jenaka.
Lensa kamera juga mengikuti penulis Nick Paumgarten yang berkeliling Kota New York. Bermodal notes kecil dan pertanyaan besar, Nick mencari warga yang bersedia diwawancarai mengenai isu politik di Amerika Serikat yang saat itu tengah panas dan memecah belah masyarakat.
Namun, sebagai sebuah karya film, dokumenter berdurasi 90 menit ini mendapatkan catatan kritis. Sebagai dokumenter soal media legendaris, durasinya masih kurang karena banyaknya cerita yang hanya digali di permukaan saja.
Rangkaian wawancara dengan banyak kepala terasa seperti "kain perca" yang ditempel begitu saja tanpa benang merah yang menyatukan secara kuat. Sinematografinya pun dinilai datar, tanpa permainan emosi atau visual yang mencengangkan, hanya mengandalkan padu padan gambar dokumentasi dan video ilustrasi.
Yang paling disayangkan adalah hilangnya dinamika nyata di ruang redaksi. Film ini menampilkan suasana yang sangat tenang dan penuh senyuman, bahkan saat Pemimpin Redaksi David Remnick membahas rencana liputan investigasi besar.
 Review The New Yorker at 100: film ini menyuguhkan proses fact checking yang teliti, tanpa pandang bulu, menguliti setiap kata yang dirangkai oleh para penulis. (Courtesy of Netflix)
Review The New Yorker at 100: film ini menyuguhkan proses fact checking yang teliti, tanpa pandang bulu, menguliti setiap kata yang dirangkai oleh para penulis. (Courtesy of Netflix)
Tak ada perdebatan tajam atau adu argumen yang biasanya menjadi "nyawa" di balik meja redaksi saat membahas isu sensitif. Semuanya tampak terlalu mudah dan kurang serius bagi sebuah media yang dikenal dengan standar intelektualnya yang tinggi.
Meski begitu, film ini menyuguhkan proses fact checking yang teliti, tanpa pandang bulu, menguliti setiap kata yang dirangkai oleh para penulis. Proses ini memastikan bahwa setiap detail cerita yang disuguhkan ke pembaca adalah benar belaka, bukan khayalan semata, walau New Yorker memang pernah beberapa kali kecolongan.
Satu pertanyaan besar yang gagal dijawab oleh dokumenter Marshall Curry adalah: Bagaimana New Yorker bisa selamat dan tetap "sakti" di tengah suramnya bisnis media saat ini?
Di era pasca-pandemi COVID-19, banyak media berguguran akibat oplah yang menurun dan anjloknya pendapatan iklan. Banyak jurnalis kehilangan pekerjaan, tapi New Yorker seolah berdiri di atas awan.
Meskipun David Remnick sempat menyinggung soal model bisnis yang mengandalkan iklan dan langganan, film ini tidak menggali lebih dalam strategi konkret mereka. Produk yang bagus hanyalah satu sisi koin; menjualnya adalah sisi lain yang lebih sulit.
 Review film The New Yorker at 100: Dokumenter ini tidak memberikan jawaban gamblang mengapa pasar tetap menerima New Yorker sementara media keren lainnya seperti Majalah Pantau harus gulung tikar. (Courtesy of Netflix)
Review film The New Yorker at 100: Dokumenter ini tidak memberikan jawaban gamblang mengapa pasar tetap menerima New Yorker sementara media keren lainnya seperti Majalah Pantau harus gulung tikar. (Courtesy of Netflix)
Dokumenter ini tidak memberikan jawaban gamblang mengapa pasar tetap menerima New Yorker sementara media keren lainnya seperti Majalah Pantau harus gulung tikar.
Marshall Curry memang mengakui bahwa film ini adalah bentuk penghormatannya sebagai pembaca setia sejak kecil yang awalnya terintimidasi oleh "kerumunan kata" di New Yorker sebelum akhirnya jatuh cinta pada kartun dan artikel panjangnya.
Curry juga menghadirkan wawancara dengan berbagai figur publik yang terinspirasi oleh majalah ini dalam kehidupan mereka.
Pada akhirnya, bagi yang tertarik mengenai media massa, menyukai seni, dan kesusastraan, New Yorker at 100 tetaplah sebuah tontonan yang layak disimak.
(end)